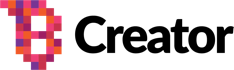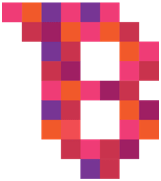Brilio.net - Bersepeda bisa dibilang salah satu olahraga paling murah, menyenangkan dan tentu saja menyehatkan. Sebab hampir semua orang bisa memiliki sepeda dan menggunakannya tak cuma untuk berolahraga, namun beraktivitas harian. Jadi tak heran jika sampai sekarang masih banyak orang sangat hobi bersepeda untuk sekadar jalan-jalan, olahraga, bahkan untuk berangkat ke kantor yang sampai kini hits dikenal dengan istilah bike to work.
Nah, berbicara tentang sepeda di Indonesia, tentu Jogja tak boleh dilupakan. Tercatat sejak era 1980, kota ini dulunya memang dipadati banyak pesepeda setiap harinya. Bahkan di tahun 90-an saja, masih sangat banyak para pekerja dan pelajar yang selalu terlihat saban hari bersepeda di penjuru-penjuru kota Jogja.
Di Jogja ini pula, sebenarnya terdapat banyak sosok inspiratif pesepeda namun tak banyak terdengar gaungnya. Salah satunya sebut saja adalah Pakdjo. Pria berusia kepala empat ini punya kisah mengagumkan ketika dia muda. Saat berusia dua puluhan, dia pernah bersepeda dari Jogja hingga Tibet, sebuah dataran tinggi di China yang berbatasan dengan Myanmar, India, Bhutan, dan Nepal.
Kepada brilio.net belum lama ini, Pakdjo membagikan sedikit banyak pengalaman serunya bersepeda Jogja-Tibet-Jogja kala itu. Pakdjo mengaku tak pernah berani menceritakan itu kepada media, sebab dia tak bisa membuktikan apa-apa terutama lewat dokumentasi foto. Saat itu Pakdjo cuma bermodalkan sedikit uang dan sepeda standar yang dirasanya layak untuk bepergian jauh.
Cerita itu berawal dari saat Pakdjo masih duduk di bangku SMA, sekira tahun 88-89. Menurutnya kala itu dia selalu iri kepada teman-temannya yang selalu pamer ketika liburan pasti pergi ke luar negeri seperti Australia, Singapura. Padahal saat itu Pakdjo termasuk golongan dari keluarga yang pas-pasan dan tak memungkinkan untuk 'ikut tren' liburan ke luar negeri seperti teman-temannya.
Namun 'dendam' itu akhirnya baru bisa dibayar oleh Pakdjo beberapa tahun ke depan. Ketika dia sudah bekerja kantoran sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dia mencoba untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara selama dua tahun. Saat itu dirinya masih berstatus sebagai PNS di Kelurahan Sosromenduran sebagai sekretaris lurah.
"Setelah cuti diterima, saya berangkat Oktober akhir tahun 97, pas masih umur 25 kalau nggak salah pada waktu itu. Saya sampai menggadaikan sepeda motor Suzuki RC80 untuk mengurus visa dan paspor," kata pria yang bernama asli Yohannes ini ketika membuka obrolan dengan brilio.net di kantornya.
Pakdjo dulu menggunakan sepeda merek Gary Fisher dan cuma modal uang saku sekitar Rp 2.500.000 saja. Perjalanan pulang pergi Pakdjo saat itu memakan waktu 1,5 tahun.
"Pokoknya saya pas berangkat itu memang sudah berencana mau jalan paling nggak sampai Trans Asia saja, akhirnya malah sampai Tibet. Awalnya rutenya dari sini (Jogja), Sumatera, dan di Sumatera berhenti agak lama karena bermasalah saya malah kecelakaan. Terus naik ke Malaysia, Vietnam, bablas sampai India langsung Tibet," ujarnya.
Sesampainya di Sumatera pun Pakdjo mengaku sempat putus asa. Sepedanya terserempet kendaraan lain lalu membuatnya harus beristirahat cukup lama karena cedera. "Zaman dulu itu lintas Sumatera jalannya kan nggak karu-karuan, jeglongannya dalam-dalam satu meteran. Jangankan sampai Malaysia, wong bisa sampai Sumatera aja dulu bangganya udah bukan main. Dan sampai Sumatera itu nggak sampai sebulan, soalnya Jogja-Jakarta dulu itu aja pas enam hari. Tapi tetap jalan santai lho ya. Capek lapar ya berhenti, makan dan istirahat secukupnya."
Selama perjalanan lintas Jawa-Sumatera, Pakdjo mengaku selalu terselamatkan dengan adanya masjid. Menurut dia, zaman itu hampir seluruh masjid dan musala sepanjang Jawa-Sumatera selalu menyediakan makanan dan tempat menginap. Selain itu Pakdjo juga tertolong oleh para sopir truk yang selalu menceritakan tentang dirinya yang bersepeda kepada warung-warung makan berikutnya. Getok tular istilahnya.
"Zaman dulu masjid dan musala itu indah. Selain tempat ibadah, tapi juga jadi tempat berlindung dan bisa sekalian numpang sarapan juga. Habis shubuhan itu mesti bisa langsung sarapan di sana. Selain itu kalau pas lagi jajan di warung yang harusnya makan keluar Rp 750, malah jadi free. Digratisin terus, karena kabar saya naik sepeda sudah diceritakan sopir-sopir truk yang beberapa hari lalu saya ketemu itu," kata Pakdjo.
foto: brilio.net 2019/agib tanjung
Menurut Pakdjo, alasan finansial memang salah satu jadi faktor utama kenapa perjalanannya juga menjadi sangat lama. Padahal menurutnya, jika dia mau 'curang', dia bisa saja setiap kota berhenti untuk meminta pesangon kepada pemerintah daerah. Terutama saat masih berada di area Indonesia.
"Di perjalanan ya kacau sekali dulu itu. Zaman segitu saya nggak punya referensi soal sepeda. Karena ya itu tadi, zaman segitu pesepeda itu lumrahnya orientasinya ya mampir ketemu pejabat-pejabat daerah, foto bersama, dikasih uang saku. Dan saya kan nggak bisa begitu. Sebabnya apa? Ya karena pada saat itu saya kan statusnya PNS dan sedang cuti di luar tanggungan negara. Ya malu lah," tegas Pakdjo.
Saat perjalanan itu pun Pakdjo tentu tak lupa untuk memberi kabar kepada keluarganya di Jogja. Selama 1,5 tahun perjalanan itu, Pakdjo cuma sempat mengirimkan surat ke Jogja dua kali saja. Pertama saat sesampainya di Malaysia, kedua saat dirinya akan melakukan perjalanan pulang dari Tibet menuju Jogja lagi.
"Itu pun dulu keluarga di rumah langsung geger banget. Soalnya pada saat itu yang dapat surat pertama kan pak dukuh. Pak dukuh dapet surat dari kantor pos cap stempelnya luar negeri dari Malaysia," ujar Pakdjo sembari tertawa lepas.
Pakdjo juga menceritakan tak malu untuk 'mengemis' di jalanan guna bertahan hidup. Namun dia tetap melakukan sesuatu yang positif dengan barang bawaannya dari Jogja, yakni wayang kulit. "Saya pede aja pokoknya, di pinggir jalan atraksi pakai wayang dan itu yang membuat saya lumayan nggak sampai kehabisan uang," kata dia.
Hampir mati gara-gara hepatitis
Melakukan perjalanan jauh tentu saja tak lepas dari beragam pengalaman. Menarik tak cuma soal sukanya saja, tapi juga dukanya. Dengan mengayuh sepeda sepanjang 9,610 kilometer (data dihitung via Google Map), Pakdjo punya pengalaman buruk sebelum pada akhirnya merampungkan misinya ke Tibet.
"Pada saat itu saya mendapat cuaca di India dan Tibet yang terdingin. Karena pada saat itu saya ingat banget di India aja kalau hujan sedikit aja pasti langsung banjir lumpur sampai selutut. Terus jangan bayangkan kayak sekarang, pesepeda bisa pada gagah-gagah gitu sampai ke Tibet. Lha dulu sepeda saya gear-nya cuma 6 dan tidak membawa tool kit memadai. Jadi jangan kaget kalau ban meledak ya sering banget saya isi damen (batang padi)," kata Pakdjo melanjutkan ceritanya.
Menurut Pakdjo, Tibet pun sebenarnya bukan tujuan utamanya. Tibet menjadi lokasi terakhir yang secara spontan ingin Pakdjo lakukan. Alasannya dia tidak bisa masuk ke di India karena visanya tidak tembus. Selama di perjalanan itu tadi Pakdjo 'dikompori' oleh teman-teman kenalan barunya untuk sekalian saja mencoba ke Tibet, meski risikonya sangat berbahaya dan nyawa jadi taruhannya.
"Sebenarnya pun nggak kepikiran ke Tibet, karena saya rencana sudah mau pulang pada waktu itu. Tapi karena disemangati teman-teman baru yang ada di sana, saya lanjut aja ke Tibet, tapi kalau nggak mati! Ya saya pikir, ya sudah sampai sini masa nggak coba lanjut. Kalau mati ya sudah, nasib," papar Pakdjo.
Halangan pun tak sampai di situ. Ketika sudah mulai memasuki daerah Chengguan, Pakdjo harus mengalami sakit keras. Pakdjo didiagnosis hepatitis setelah diperiksa dokter setempat. Penyebabnya di beberapa kota sebelumnya Pakdjo selalu sembarangan makan dan minum.
"Jadi saat itu saya posisi dari Burma (Myanmar), kemudian ke arah Arunachal Pradesh terus sampai Chengguan dan saya ambruk total selama tiga hari di losmen. Saya muntah-muntah terus jadinya lemes banget. Pertama panas dingin badannya tapi campur diare berat dan tiba-tiba dari kuku, mata sampai kulit ya jadi kuning. Tulang dada juga perih sekali kalau dipegang. Pandangan mata aja sudah nggak jelas sama sekali," cerita Pakdjo.
Akhirnya pemilik losmen memanggilkan Pakdjo seorang biksu, yang dipercaya lingkungan setempat sebagai 'orang pintar'. Pengobatannya pun sampai sekarang ini masih bikin heran bila diingat-ingat lagi oleh Pakdjo. Baginya pengobatan si biksu itu terkesan sangat magis.
"Dia membuang air liurnya ke tanah, terus dia ambil pakai jari telunjuknya, komat-kamit sebentar, terus telunjuknya tadi langsung ditempelkan ke mata saya. Nyos! Rasanya perih ngilu seluruh badan. Saya nggak habis pikir juga sampai sekarang. Wong saya hepatitis gara-gara makanan kotor kok diobati dengan cara yang mohon maaf jorok begitu? Dan sampai sekarang pun kalau saya menceritakan hal seperti ini kan pasti dianggap mistik, ya kan?" papar Pakdjo.
foto: brilio.net 2019/agib tanjung
Usai diobati sang biksu tadi, malam itu Pakdjo kemudian tertidur dan baru bangun besoknya pukul empat sore. Badannya pun sudah terasa ringan dan warna kuning di tubuhnya sudah berangsur menghilang. Sang biksu ini memang sudah tak ada lagi di losmen itu, namun si biksu ini meninggalkan kain sari warna putih polos yang sampai kini masih disimpan dengan baik oleh Pakdjo.
"Dan setelah saya diobati biksu itu tadi, saya berpikir untuk tinggal sejenak di sana dan mulai berdoa terus untuk keselamatan saya sampai pulang ke Jogja lagi. Karena saya pikir, saya bisa selamat dan nasib saya ditentukan dari tempat itu," ujarnya.
Pakdjo pun mulai melanjutkan perjalanannya ke Tibet sekaligus pulang melewati rute yang berbeda. Jika saat berangkat Pakdjo melewati Thailand, pulangnya dia memilih memutar melewati pinggiran Laos hingga ke Vietnam.
"Itulah kenapa sampai saat ini saya terkadang ndak berani cerita ke banyak orang, terutama media. Karena saya tidak ada bukti gambar, foto. Satu-satunya bukti mungkin cuma surat saya yang dulu saya kirimkan dari Malaysia kepada almarhum ayah saya. Lalu ada kain sari pemberian sang biksu hebat itu tadi. Sepeda Gary Fishernya pun sebenarnya masih ada, cuma sekarang sudah saya jual ke sahabat saya di Jogja juga," tutup Pakdjo.
Pakdjo yang lahir tahun 1971 ini sampai sekarang mengabdikan dirinya di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (Balai RSBKL) Yogyakarta sebagai salah satu staf perencana kegiatan kerja. Setiap harinya, pria yang termasuk penggagas Sego Segawe (program sepeda untuk sekolah dan bekerja) ini juga masih rutin bersepeda untuk berangkat kantor dan touring ke luar kota seorang diri.
"Terakhir akhir tahun 2017 lalu saya semingguan ke Surabaya. Ya sendirian juga, hahaha!" imbuh Pakdjo.
Recommended By Editor
- Becak Pustaka Mbah Sutopo, koleksi ratusan buku untuk penumpang
- 'Permataku', sholawatan lewat musik pop rock ala Gus Fuad Plered
- Warteg Glagahsari, warung Tegal legendaris pertama di Jogja
- Blusukan ke dapur Roti Djoen, roti legendarisnya kota Jogja
- Kisah penyelamat penyu di pantai selatan Jogja ini bikin salut