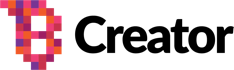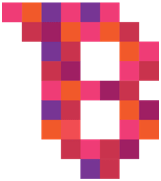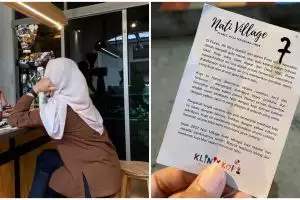Brilio.net - Mbilung mak jegagik sudah duduk selow di bangku angkringan Si Mbah. Tangannya langsung mengambil bungkusan nasi kucing lauk sambal teri. Mahasiswa sebuah kampus negeri ini langganan angkringan demi hidup ngirit. Di sela-sela makan, dia mulai curhat.
“Coba rasakan apa yang saya alami, Mbah. Kalau diam saja lima menit terus bosan, obatnya main Facebook. Kalau sudah lima menit main Facebook terus bosan, Facebook saya matikan. Tapi kalau sudah lima menit diam saja bosan pengen main Facebook lagi. Begitu terus. Itu sebenarnya penyakit apa?” Mbilung nyerocos.
Si Mbah, dasar sudah kepala tujuh tidak paham dremimilan Mbilung. Dia sibuk mengiris gula Jawa tipis-tipis buat dilarutkan ke geprekan jahe yang sudah dibakar. Proses kimiawi bakaran jahe sebelum dilarutkan ke air panas, terbukti berhasil memaksimalkan aroma dan rasanya.
Angkringan Si Mbah ini spesial wedang jahenya. Konon air jahe dalam ceretnya punya ramuan khusus. Ada bahan lain tak cuma air panas dan jahe, hanya Si Mbah yang tahu.
Wedang jahe menjadi suguhan khas angkringan. (Foto Brilio.net)
Buat Si Mbah yang setiap hari berkutat dengan wedang, gorengan, sate usus, sate ndog puyuh atau tahu bacem, jelas nggak terlalu paham Facebook. Si Mbah tahunya, ada perilaku berbeda di warung angkringannya sebelum dan sesudah Facebook.
#SebelumFacebook. Tidak ada orang yang jeprat-jepret motret sembarang makanan atau wedang di angkringan. Semakin kemebul wedang, semakin keren jepretannya. Semakin klomoh tahu dan tempe bacem, semakin indah jepretannya. Cekrek. Upload.
#SebelumFacebook. Betapa level narsisme pelanggan angkringan meningkat berlipat. Narsisme sudah jadi epidemi. Dulu orang hanya makan dan minum sekarang nongkrong di angkringan pun minta dijepret. Sik, sik, sik. Yak Siap. Jepret. Ji ro lu. Jepret. Angkringan apa studio foto?
Luput disadari Si Mbah, angkringan yang dia dasari tiap sore sampai tengah malam itulah Facebook sesungguhnya. The real social life. Di warung dasarannya itu berkumpul orang yang belum saling kenal. Dari berbagai macam latar belakang. Ada mahasiswa, ada birokrat, ada intelektual, ada wong cilik, ada wong licik, ada wong sumuk, ada wong umuk. Sesekali ada gelandangan tanpa sanak tanpa kadang.
Di angkringan Si Mbah jagongannya guyub. Kadang debat, tapi tidak sampai eker-ekeran. Obrolannya adem dan tentrem.
“Yo wis dilereni wae sing dolanan Facebook,” Si Mbah menjawab Mbilung sekenanya.
“Itu namanya bukan solusi,” Mbilung mangkin mangkel dengar jawaban Si Mbah.
“Coba tanyaken ke Si Bung, itu.”
Saya mak jegagik disebut-sebut Si Mbah. Padahal lagi nyibak baceman tahu, mencari yang minyaknya sedikit lebih kering. Biar aman kolesterol.
Status saya yang wartawan dipikirnya tahu segala. Padahal pada masa pasca-kebenaran ini, bukan seperti itu keadaan.
Demi guyubnya angkringan, lebih pas mencarikan solusi Mbilung, saya mulai browsing mencari jawaban.
Saya balik tanya Mbilung buat tahu habitnya main Facebook. Kali ini Mbilung serius. Tatapan matanya ke saya. “Ya biasa, scroll down, scroll down sampai capek. Kadang upload foto sendiri, kadang upload apa saja yang bisa diupload. Buat hiburan,” jawab Mbilung.
“Kamu nggak salah. Apa yang kamu lakukan dengan Facebook itu sebenarnya biasa.”
“Nggak salah gimana?” Mbilung nggak mengira jawaban saya.
Begini. Sebenarnya membagikan kisah atau gambar kehidupan sehari-hari itu tidak bermula dengan kehadiran Facebook atau kawan-kawannya semacam Twitter dan Instagram. Perilaku itu sudah ada dari dulu.
Kata orang, media sosial menjadikan manusia narsis. Tetapi kalau baca buku Qualified Self (2018), pengarangnya Lee Humphreys punya cara pandang lain. Menurut Humphreys yang meneliti penggunaan handphone sejak 2001, membagikan detail kehidupan seperti makanan, foto diri, foto liburan, bukan berawal dari media sosial. Sejak abad 18, orang sudah menggunakan buku harian, scrapbooks atau album foto untuk aktivitas sama.
“Sejak teknologi memudahkan selfie itu bukanlah penyebab kita menjadi narsis. Itu bagian sejarah panjang tentang bagaimana orang mendokumentasikan keseharian hidup mereka,” saya mengutip Humphreys.
Dalam bukunya dia memaparkan contoh-contoh buku harian abad ke-18 memiliki kemiripan dengan cuitan di Twitter. Dulu pun orang terbiasa membagikan album fotonya kepada keluarga dan teman. Pendeknya, kalau orang sekarang mengenal jejak digital, zaman dulu manusia sudah mendokumentasikan jejak kehidupannya.
“Berarti apa yang saya paparkan tadi di awal bukan penyakit dong?” Mbilung masih penasaran.
Bukan. Tapi beda halnya kalau sudah ketagihan. Namanya kalau ketagihan, nalar berpikir bisa mati. Kamu bisa menjadi apa yang diistilahkan sekarang sebagai zombie karena media sosial.
“Zombie? Kayak Walking Dead itu, kayak Train to Busan?” Mbilung makin antusias. “Saya pernah baca. Katanya di Chongqing, China, ada trotoar yang khusus didesain buat mereka yang lagi jalan sambil main HP. Zombie berhape.”
Ragam makanan yang dijajakan di angkringan. (Foto Brilio.net)
Saya menjelaskan bagaimana ketagihan Facebook bisa dengan mudah mematikan nalar.
Dahulu selama dua abad, ke-18 dan 19, kultur komunikasi didominasi tulisan. Budaya membaca tinggi. Seiring lahirnya televisi seperti ditulis Neil Postman dalam Amusing Ourselves to Death (1985), terjadi pergeseran dari budaya tulis ke budaya gambar. Artinya terjadi pergeseran dari rasionalitas ke dalam emosi. Dari eksposisi ke hiburan. Ketika gambar mendominasi, Postman mengatakan, tidak ada pola pikir rasional. Orang tidak bisa berpikir dengan gambar.
Kemudian lahirlah internet. Pada mulanya internet hadir dengan harapan alternatif terhadap cengkeraman televisi di masyarakat. Memang awalnya internet berbasis teks, dijadikan alat untuk kepentingan pengetahuan. Internet banyak dipakai di kampus-kampus top di seluruh dunia untuk sarana diskusi, majalah elektronik, mailing list dan forum akademis. Itu semua proyek-proyek intelektual.
Belakangan ini dengan kehadiran internet, datanglah media sosial, seperti NICA membonceng sekutu. Baik Facebook atau Instagram sama-sama memusatkan perhatian ke video dan gambar. Dopamin menimbulkan kepuasan ketika kamu memberi atau mendapat like, membagikan postingan atau postinganmu dibagikan. Emosi ini mengalahkan pola pikir rasional. Alih-alih mencari kepuasan pengetahuan, otak dirangsang untuk mendapat penerimaan dari khalayak.
Ini seperti membenarkan filsuf Prancis Guy Debord yang menulis dalam Society of The Spectacle (1967). Dulunya dalam kehidupan sosial manusia hanya mengenal konsep menjadi (being) kemudian saya punya apa (having) kemudian muncullah konsep mempertontonkan (appearing). Dalam dunia kapitalis sekarang ini, yang lebih berperan adalah mempertontonkan diri. Ingin tampak kaya, tampak gembira, tampak pintar dan sebagainya. “Kamu termasuk bagian kelompok yang pengen menampakkan diri itu, Lung.”
Maka kemudian yang terjadi kamu akan terus melakukan scroll, scroll, scroll, ketagihan. “Kamu sudah terkena sindrom ini: sindrom scrolling zombie. Inilah bahayanya,” kata saya kepada Mbilung. Perusahaan keamanan internet McAfee memperkenalkan istilah sindrom scrolling zombie pada 2016.
Mbilung, mungkin karena kebiasaannya ngantuk saat kuliah, cuma manggut-manggut saja.
“Lha yen zombie kuwi isih iso mbayar utang ora Bung,” sahut Si Mbah.
“Nggak usah nyindir-nyindir Mbah. Berapa semuanya. Jahe satu, nasi kucing dua, tempe dua,” Mbilung minta totalan. “Jahe telung ewu, sego patang ewu, tempe telung ewu. Kabeh 10 ewu.”
“Tempe setipis ATM kok mahal,” protes Mbilung. Si Mbah mrenges.
Oleh: Titis Widyatmoko