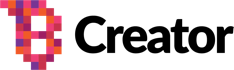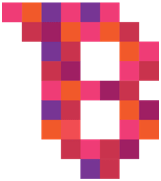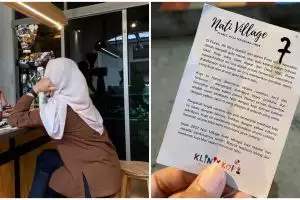Brilio.net - Sejauh enam kilometer tenggara pusat kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat (Jogja), Kuta Gede bermula di pertigaan Jalan Imogiri Timur. Dari pertigaan jika ditarik garis lurus ke selatan, mengarah ke makam para raja Mataram di perbukitan Imogiri.
Pertigaan itu sekarang makin bising. Persis di tusuk sate dari timur, tampak warung angkringan yang setiap malam tak pernah sepi. Nasi bakarnya lezat. Wedang jahenya nikmat. Sesekali masih tersedia saren atau dideh, lauk berbahan darah ayam beku yang tak boleh oleh Islam.
Di seberang warung agak ke selatan berdiri minimarket berjaringan. Di halamannya teronggok peti kemas tempat berjualan martabak dari jenama milik anak presiden.
Berjalan ke arah timur dari pertigaan, mulai memasuki wilayah Kuta Gede. Sebelum jembatan Gajah Wong -satu dari tiga kali besar yang mengiris Jogja dari utara ke selatan, selain Winongo dan Code- berdiri bangunan-bangunan megah milik orang kaya Kuta Gede di masa silam. Sejarah mencatat Kuta Gede pernah menjadi pusat perdagangan permata, emas, perak terbesar di Hindia Belanda.
Bangunan mashyur pada zamannya itu kini bersalin macam rupa, ada toko coklat, restoran, penginapan, cabang bank, kebanyakan pusat kerajinan perak.
Pada masa kolonial, advertensi, pamflet dan itinerari wisata ke Jawa selalu mencantumkan Kuta Gede sebagai tujuan wisata. Hingga dua dekade lalu, bus-bus wisata besar masih lalu-lalang di jalanan utama yang hanya selebar lima meter. Itulah masa keemasan industri kerajinan perak Kuta Gede. Toko-toko kerajinan perak yang bertebaran, di barat maupun timur Jembatan Gajah Wong tidak pernah tidak meriah. Hingga kemudian zaman mengubah peruntungan para pengrajin selaka.
Murahnya perak impor dari China menjatuhkan pasaran perak Kuta Gede. Sistem jual beli online turut membuat toko ngelangut. Seorang teman, pengrajin perak Kuta Gede bercerita, beberapa rekannya sudah hijrah mencari nasib lebih baik ke Batu Bulan, sentra perak nun di Pulau Dewata sana.
Sebelah barat Jembatan Gajah Wong, dulu sebelum 1925 hanya boleh dilewati kendaraan raja dan pengiringnya. Orang biasa dilarang lewat. Jalan itu sekarang bernama Mondorakan, diambil dari nama Ki Ageng Mondoroko atau Ki Juru Martani yang bersama leluhur raja Mataram, Ki Ageng Pemanahan membabat alas Mentaok, cikal bakal Kuta Gede.
Di selatan jalan selepas jembatan, ada restoran berarsitektur bangunan panggung. Restoran mewah, tentu saja harga menunya mahal-mahal. Seringkali restoran itu didatangi turis bule, atau rombongan pelancong dari luar Jogja. Warga lokal, yang berkantong cekak, ciut untuk memuaskan lidah dan perut di sana.
Di seberang restoran sedikit ke timur, berdiri bekas rumah orang kaya Kalang yang dibeli dosen UGM setelah gempa Jogja. Usai direnovasi, rumah padat ornamen dulunya milik juragan Proyodrono itu menjadi kafe dan sering dipakai tempat diskusi. Di saluran hiburan sebuah maskapai asing belum lama ini, saya menonton dokumenter tentang rumah ini berjudul A House of Its Time, Indonesia: Javanese Eclectic. Tentu saja, empunya rumah yang juga dikenal sebagai wartawan kawakan itu ikut diwawancara dalam film itu.
Beranjak ke timur, jalanan nyaris tidak berubah dibandingkan deskripsi Van Mook saat menulis tentang Kuta Gede pada 1926. Lebih dikenal sebagai garis imajiner daripada sesosok manusia, Van Mook meneliti Kuta Gede saat berusia 27 tahun. Ketika itu dia penasihat agraria Raja Jogja.
Saya kutipkan penggambaran Van Mook di sini: “Jalan utama sempit tanpa pohon-pohon, di kanan kiri terkurung oleh deretan rumah dan tembok, yang hanya diselingi lorong dan gang kecil; toko-toko kecil dan besar dengan jendela yang terbuka ke atas, beberapa rumah “tuan besar” yang dibangun secara rumah “Eropa”, lebih banyak digunakan untuk pameran daripada untuk rumah tinggal, dan banyak tembok-tembok tanpa pintu: di belakang tembok ini terdapat rumah-rumah kuno (dan indah) dari kayu dengan berbagai bagiannya mengelilingi taman-taman dalam kecil penuh pohon jeruk.”
Jalan utama itu sampai sekarang masih sama sempit. Kalau satu mobil berhenti, secara cepat menimbulkan antrean di belakangnya. Aspalnya bopeng di tengah, bekas galian saluran air.
Kawasan Pasar Kuta Gede yang selalu ramai setiap hari pasaran legi. (Foto Brilio.net/Titis Widyatmoko)
Zaman kemudian mengubah tembok-tembok dalam penggambaran Van Mook itu, sebagian besar menjadi pertokoan. Di beberapa bagian pemilik toko mulai merombak bangunan, memundurkan tembok sekadar memberi ruang untuk parkir motor pengunjung. Di antara deretan kios, teristimewa warung oleh-oleh karena masih menjual kipo, makanan khas Kuta Gede.
Agak sulit menjelaskan kipo yang bentuknya kecil-kecil itu. Ketidakjelasan definisi itu pula yang berhasil membentuk namanya. Konon dulu orang bertanya-tanya usai melihat bentuk makanan itu. Mereka bertanya iki opo (ini apa). Lantas jadilah namanya: kipo.
Pada intinya, kipo terbuat dari kulit tepung ketan berisi kelapa parut dengan gula merah, kemudian dibakar. Satu bijinya sebesar jari jempol. Per bungkus seharga Rp 2.500 diisi lima biji kipo.
Bergerak ke timur lagi, di selatan pasar ada Masjid Gede Mataram. Salah satu yang tertua di Jogja. Masjid ini dibangun di zaman Sultan Agung, tahun 1600-an. Di saat banyak warga sekitar masih Hindu atau Buddha. Di sekitar masjid masih ada makam pendiri Mataram yang dikeramatkan. Kuburan itu tidak dapat dikunjungi setiap hari. Ada hari-hari tertentu dan jam-jam tertentu. Kamis dari jam 9 pagi sampai 10 pagi dan hari Jumat dari jam 1 siang sampai jam 3 malam.
Para pengunjung kuburan meletakkan bunga dan makanan dan membakar menyan untuk mengirim doa kepada raja-raja lama. Masjid dan makam itu pula yang dulunya menciptakan keunikan Kuta Gede: status tanah yang kacau dan ruwet karena tumpang tindih dimiliki Kesultanan Jogja dan Kasunanan Solo. Di era modern pun, kekusutan tetap bertahan karena ada wilayah Kuta Gede yang didaku Kotamadya Yogyakarta, ada pula yang masuk Kabupaten Bantul
Kuta Gede sekarang, menjadi satu-satunya ibu kota Mataram lama yang masih menampakkan sisa-sisa sebuah kota. Tidak seperti Kerta, Plered, atau Pajang yang musnah tertelan sawah dan rumah. Atau Kartasura yang tinggal menyisakan tembok bata bekas istana negara.
Zaman boleh mengubah napas Kuta Gede, tetapi tidak riwayatnya. Menjejak Kuta Gede, melayangkan angan ke ratusan tahun lalu, kita akan merasakan aura kemegahan, keagungan, kebesaran, dan kemewahan Kuta Gede.
Oleh: Titis Widyatmoko